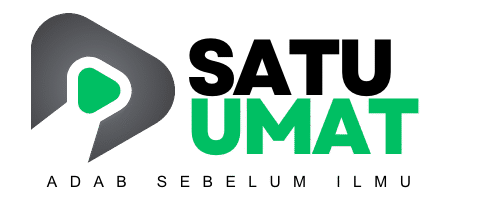Khalifah Umar Ibnu Khattab adalah sosok khalifah yang sangat
sederhana. Saking sederhananya sampai-sampai orang yang menjumpainya tak percaya, kalau yang tengah dihadapi adalah seorang khalifah yang
kekuasaannya meliputi jazirah Arabia, bahkan sampai ke daratan Afrika.
Namun di balik kekuasaan yang sangat luas tersebut, sikap Umar Ibn
Khattab sangat bertolak belakang. Ia hidup dalam kesederhanaan dan
kejujuran. Setiap uang negara yang dipakainya senantiasa dipergunakan
untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.
Kesederhanaan Sayidina Umar terlihat dari tempat tinggal dan pengadilannya yang seperti layaknya rakyat kebanyakan.
Satu saat seorang pedagang Yahudi dari Mesir datang ke Madinah. Ia ingin menemui Khalifah Umar. Namun ia sungguh belum tahu, yang mana Umar bin Khattab, kepala pemerintaahan negeri Islam yang wilayahnya makin meluas itu. Kepada seseorang yang ia temui di perjalanan, ia bertanya, “Di manakah istana raja negeri ini?”
Orang itu menjawab, “Lepas Dhuhur nanti, ia akan berada di tempat istirahatnya di depan masjid. Dekat pohon kurma. Jika kau ingin menemuinya, pergilah ke tempat itu.”
Yahudi itu sesunguhnya membayangkan, alangkah indahnya istana Khalifah,
dihiasi kebun kurma yang rindang, tempat berteduh merintang-rintang waktu.
Maka tatkala tiba di muka masjid, ia kebingungan. Sebab di situ tidak ada
bangunan megah yang mirip istana. Memang ada pohon kurma, tetapi cuma
sebatang saja.
Dan di bawahnya, tampak seorang lelaki kekar dengan jubah yang sudah luntur
warnanya tengah tidur-tidur ayam. Yahudi itu mendatangainya dan bertanya,
“Maaf, saya mau berjumpa dengan Umar bin Khattab.”
Sambil bangkit dan tersenyum Umar menjawab, “Akulah Umar bin Khattab.”
Yahudi itu terbengong-bengong, “Maksud saya Umar yang khalifah, pemimpin
negeri ini.”
Umar menjelaskan, “Akulah Khalifah, pemimpin negeri ini.”
Yahudi itu makin kaget. Mulutnya terkatup rapat, tidak bisa bicara. Ia
membandingkan dengan para rahib Yahudi yang hidupnya serba gemerlapan dan
para raja Israel yang istananya juga tak kalah agung.
Sungguh tidak masuk akal, kalau ada seorang pemimpin dari suatu negara yang
begitu besar, tempat istirahatnya hanya di atas selembar tikar, di bawah
pohon kurma di tengah langit yang terbuka.
“Di manakah istana Tuan?” tanya sang Yahudi.
Umar menuding, “Di sudut jalan itu. Bangunan nomor tiga dari yang terakhir,
kalau yang kau maksudkan adalah kediamanku.”
“Maksud Tuan, yang kecil dan kusam itu?” si Yahudi tambah keheranan.
“Ya. Namun itu bukan istanaku. Sebab istanaku berada dalam hati yang
tenteram dengan ibadah kepada Allah swt,” Sambut Umar sembari tetap
tersenyum.
Yahudi itu kian tertunduk. Kedatangannya yang tadinya hendak melampiaskan
kemarahan dan tuntutan-tuntutan, berubah menjadi kepasrahan dengan segenap
jiwa raga.
Sambil matanya berkaca-kaca ia berkata, “Tuan saksikanlah, sejak hari ini
saya meyakini kebenaran agama Islam. Izinkah saya memeluk Islam sampai
mati.”
Setelah mengikrarkan syahadat, orang itu akhirnya pergi dengan dadanya
dipenuhi suka cita. Umar sendiri terus memperhatikannya dengan baik-baik.
Ia memandangi pohon kurma di hadapannya. Ia juga memandangi pakaiannya
sendiri.
Baginya, sebagai seorang pemimpin penampilannya harus benar-benar
mencerminkan kesederhanaan. Baginya, apalah artinya sebuah kekuasaan jika
hanya harus menyakiti umatnya yang banyak? (taryono asa/dari berbagai sumber)